FATHAN
Pias gemulai redup menawanku
Menciptakan siluet bayang-bayang pemenuh kalbu
Kelu…
Kenapa aku teramat kelu dan malu?
Ah… itukah caraku memilikimu?
Kuhentikan coretan pena dibukuku. Kupandang panggung di depanku,
tempat berlatih beberapa anggota teater yang kupimpin.
Retno, Gadis berlesung pipi, bermata bulat, dan selalu berhijab. Dia
juga ada di sana. Dialah yang sering kali membuatku betah menatap tempat dia
berada. Dialah pengisi imajinasiku. Dialah puisi-puisiku.
“Fathan!”
Sapaan Gavin membuatku seketika menutup buku. Mengalihkan
pandangan menerawang pada sosok tinggi ceking yang baru saja duduk di
sampingku.
“Tentang tawaran mengisi acara Festival Teater di SMA 37, pihak
panitia menanyakan apakah kita bisa?”
Aku tak langsung menyahut. Karena aku tahu, dia masih punya
lanjutannya.
“Aku jawab bisa, karena kemarin kamu jawab begitu.”
Aku mengangguk.
“Menurutmu, kita perlu datang semua atau hanya beberapa saja?”
“Aku rasa, enam atau delapan cukup. Nanti, kalau terlalu banyak,
malah merepotkan penyelenggara,” jawabku lirih.
Giliran Gavin yang mengangguk. “Oke, kalau begitu tinggal
menentukan siapa saja yang ikut.”
Kutatap lagi area panggung. Mereka sedang tertawa-tawa, termasuk
Retno. Ah, lesung pipi itu membuatku sulit bernapas dan kehilangan kendali
untuk tak terpaku padanya.
“Mending, umumin sekarang saja.” Gavin lagi-lagi berhasil
menolongku.
Aku berdiri dan menepuk telapak tanganku untuk mencari perhatian. “Sorry, bisa berkumpul sebentar?”
Para anggota teater bergerak ke tepi panggung, mencari tempat
duduk yang nyaman. Semua menatapku yang memilih tetap di bawah.
Aku berdehem sekali. “Hari minggu depan ada acara Festival Teater
di SMA 37. Rencananya, aku, Gavin dan empat orang lain akan membantu mengisi
acara tersebut. Jadi, kira-kira siapa yang bersedia membantu?”
Retno mengangkat tangannya, “Aku nggak ada acara. Aku bisa ikut.”
Suaranya yang merdu membuatku seperti merasakan sejuknya embun
pagi.
Alih-alih terlalu gugup karena baru saja bersirebok dengan
padangan Retno, aku langsung mengalihkan tatapan pada lantai.
“Aku juga bisa.”
Suara Bimo mengembalikan perhatianku. Dan beberapa orang mulai
mengajukan diri.
“Oke, jadi yang akan ikut kami adalah Retno.” Kupandang sekilas
cewek itu. Dia tersenyum ramah padaku. “Bimo, Satria, dan Sinta,” lanjutku
tanpa mau terlalu lama menikmati senyumannya.
Mereka yang kusebut mengangguk mantap.
“Acara akan diadakan jam Sembilan pagi.” Gavin mengambil alih.
“Kita harus sudah siap di lokasi setengah jam sebelumnya. Diharap, jangat
telat. Oke, guys!”
“Oke!” jawab empat orang tersebut serempak.
“Baiklah, latihan hari ini cukup. Sampai ketemu hari kamis.” Aku
mengakhiri sesi latihan.
Beberapa dari mereka langsung meloncat turun dari panggung. Tapi,
untuk Retno tentu saja tidak. Kuikuti langkahnya menuju tangga. Dan tak
kusangka dia menghampiriku.
“Mas Fathan, kira-kira topik yang akan kita bicarakan nanti apa?”
tanyanya dengan suara lembut.
Aku terdiam sesaat, karena tenggorokanku tiba-tiba terasa kering.
“Em… mungkin, bisa tentang sejarah teater, atau kamu punya ide lain.” Kulirik
dia sekilas.
Dia tersenyum lagi. Ya Tuhan, kenapa senyumnya membuatku sesak
napas?
“Aku akan pikirkan ide lain. Ini pengalaman pertamaku mengikuti
acara seperti ini. Semoga, aku bisa membantu dengan baik.” Dia tampak sangat
bersemangat.
Kenapa aku selalu tak berani membalas tatapannya? “Iya.” Hanya
jawaban pendek yang berhasil keluar dari bibirku.
Setelah itu, kulihat dia bergerak pergi menjauhiku. Dan saat
itulah baru kuangkat wajahku. Kutatap langkah-langkah mantapnya yang tetap
terlihat gemulai. Rok lebarnya tampak berayun bersama jilbab biru laut senada
dengan kemeja yang dikenakannya.
Tanpa sadar, aku menghela napas lega. Tapi, ada perasaan hampa
saat dia menghilang di ujung pintu ruang latihan. Inikah rasanya mengagumi
seseorang tanpa berani mengatakannya?
***
HANNA
Kubuka pintu café.
Seperti biasa, sapaan selamat datang dari para pelayan langsung menyambutku.
Ini bukan khusus untukku, tapi untuk semua pengunjung.
Barry selalu bilang, itu adalah salah satu cara agar pengunjung
merasa di terima di tempatnya.
Aku tak memilih duduk di sofa hitam atau kursi kayu yang
melingkari meja berbentuk lingkaran. Aku langsung menghampiri meja bar tempat
Om Han – barista café ini meracik
kopi pesanan.
“Cappuccino, Hanna?”
tanyanya dengan senyum mengembang padaku.
Aku duduk di kursi tinggi, lalu mengangguk ke arah Om Han. Dia
terlalu hafal dengan seleraku.
“Barry sejak tadi pergi. Mungkin, sebentar lagi kembali,” lanjutnya
tanpa kutanya.
Aku hanya tersenyum pendek sambil menyalakan laptop. Membuka file tempatku menyimpan desain layout untuk edisi majalah minggu depan.
Bekerja sebagai layouter
di majalah seperti ini kadang membuatku bertemu karya master peace dari pujangga belum punya nama. Seperti puisi yang
sedang kubaca ini.
Pias gemulai redup menawanku
Menciptakan siluet bayang-bayang pemenuh kalbu
Kelu…
Kenapa aku teramat kelu dan malu?
Ah… itukah caraku memilikimu?
Aku mengigit bibirku sendiri. Sekali lagi kulirik nama penulisnya,
Tan. Rasa penasaranku pada sosok ini kembali memuncak. Dia selalu berhasil
membawaku pada imaji dan debaran yang mengagumkan.
“Halo, beib.”
Sapaan mesra Barry, membuatku keluar dari ruang yang selalu tercipta
saat aku berkutat dengan puisi-puisi Tan.
“Lembur lagi?” tanyanya sambil mengacungkan telunjuknya pada Om
Han, tanda dia meminta secangkir Latte
kegemarannya.
“Nggak, cuma memeriksa kerjaan doang. Dari mana?” kuputar tubuhku
menghadap ke arahnya.
Tanganku yang masih berada di atas meja bar─digenggamnya.
“Dari tempat teman.”
Kutangkap kilatan tak nyaman di pupil matanya.
“Teman?”
Barry mengangguk. Sesaat, dia melepaskan genggamannya dan beralih
pada gelas latte.
“Siapa?” lanjutku.
“Andi. Ingatkan?” Dia menjawab tanpa mau menatap ke arahku.
“Oh,” Kuputar tubuhku menghadap meja Bar. Kuangkat cangkir cappuccino-ku dan langsung kusesap
sampai tinggal setengah.
Sejujurnya, nama Andi selalu membuatku gusar. Kenapa, ya?
***
TIARA
Aku baru saja keluar dari mobil sepupuku, Barry. Dan melangkah
memasuki gerbang sekolah.
Barry adalah saudara paling nggak nyenengin.
Dulu, dia sempat tinggal di rumahku, setelah orang tuanya
meninggal. Tapi, beberapa tahun belakangan, dia memilih tinggal di apartemen
dan mengelola café ayahnya.
Kalau boleh jujur, aku lebih suka dia pergi. Habisnya, siapa yang
tahan sama cowok sensitif, pendiam dan terlalu melankolis. Kayak banci aja!
Oh, iya. Pagi ini aku terpaksa numpang mobilnya. Ini gara-gara
Mama yang maksa-maksa aku. Dan kenapa coba dia harus ke rumah pagi-pagi begitu?
“Tiara!!!”
Nah itu sura Gisel, tapi dimana dia?
“Tiara!!!”
Kuputar pandangan ke sepenjuru arah. Huft, akhirnya ketemu.
Ternyata dia berkumpul dengan anggota band-ku “Bless” di samping ring basket
sebelah utara.
“Hai, guys!”
Sapaanku disambut dengan senyum cemerlang dari mereka.
“Siap tampil?”
Pertanyaan Stevan – leader
Bless – hanya kujawab dengan anggukan.
“Tapi, setelah sesi para gank teater itu,” sahut Bim agak kesal.
Aku hanya mengangkat bahu, dan duduk di samping Gisel.
Gisel ini keyboardist,
dan aku vokalis. Sedangkan Stevan bagian gitar, ada satu lagi, “Di mana Bonbon?”
tanyaku pada Stevan.
“Hai, guys!” teriakan
Bonbon si penabuh dram–membuat kami melihat pada satu arah. Cowok kekar dengan
wajah jenaka menghampiri kami. “Sorry,
aku telat, ya?”
“Kita nggak jadi tampil pertama. Anak-anak teater itu minta
duluan. Katanya, ada acara mendadak di kampus.”
Jawaban Stevan seketika menghilangkan rasa penasaranku, sekaligus
membuat Bonbon menarik napas lega.
Sejak Bim mengatakan, kita tampil berikutnya, aku agak heran.
Padahal, beberapa hari yang lalu, panitia memberitahu, Bless tampil pertama
kali. Tahu begini, aku bisa berangkat agak santai.
“Eh, yuk ikut ngumpul. Kali aja ada yang keren.” Gisel sudah
berdiri.
“Cowok keren itu, ya Gis, kalau nggak brengsek, pasti homo!”
timpalku.
Seketika Bim tampak marah. “Maksudnya? Kamu nganggep aku brengsek,
gitu?”
Aku menyeringai geli, “Emang kamu masuk dalam jajaran cowok keren?”
“Aku ini keren!” teriaknya.
“Berarti kamu homo, dong, Bim?” Tanya Bonbon sambil tergelak.
Kamipun ikut tergelak tak kalah kencang.
Bim tampak tak senang dengan tanggapan kami. “Aku nggak homo, juga
nggak brengsek!” teriaknya. Lalu, dia melangkah menjauhi kami. Bergerak
mendekati kerumunan tempat anak-anak teater mulai mengadakan─entah apa.
Terpaksalah kami mengikutinya.
“Tiara, lihat cowok agak plontos yang tinggi tegap itu!” Gisel
menunjuk sasarannya dengan dagu. “Cool,
ya?” tanyanya setelah kami mendapat tempat duduk.
Aku mengernyit. Mengamati cowok yang dimaksud Gisel.
“Kelihatan misterius, perfectionist,
dan em… apa, ya?”
“Brengsek!” jawabku tenang.
“Kok brengsek?” dia langsung memutar tubuhnya ke arahku.
“Kalau nggak, homo.” Aku tersenyum meledek ke arah Gisel.
“Kau ini! Bisa nggak, sih, nggak sentimen sama cowok keren?”
bisiknya.
Sorry, aku
memang diciptakan untuk mem-blacklist
cowok keren di dunia ini. Karena mereka hanya para manusia yang otaknya
setengah iblis. Aku sudah membuktikannya!
Tapi, aku memilih menelan kata-kataku barusan. Aku nggak ingin mempengaruhi
mood Gisel. Gisel terlalu moody, sedikit saja tersinggung, pasti
penampilan kita nggak akan sempurna.
“Oke, yang duduk di paling belakang, yang pakai kaos hitam,
rambutnya dikucir. Yuk, maju!”
Baru saja aku diam, aku sudah dicolek Gisel lagi.
“Apa?” tanyaku.
“Suruh maju, tuh!”
Kutunjuk mukaku sendiri, “Aku?”
Gisel mengangguk mantap.
“Suruh ngapain?” Aku sama sekali nggak memperhatikan topik yang
mereka bahas. Dan sekarang, mereka menyuruhku maju ke depan. Mampus!
“Ayo, dong! Mbak, yang pakai kaos hitam, rambutnya dikucir, yang
duduk di belakang. Ayo maju!” cowok itu mengulang instruksinya.
Aku berdiri dengan ragu. Kuulangi menunjuk diriku sendiri.
“Iya, kamu!” jawabnya.
Aku menghela napas. Ternyata memang aku sasarannya. Sial!
Aku melangkah maju ke depan, dan naik ke atas panggung. Kuhampiri
cowok yang memanggilku.
“Siapa namanya?” tanyanya ceria.
“Tania.”
“Kelas?”
“XII.”
“Suka teater?”
“Nggak!”
“Ooh…” reaksi cowok di sampingku ini benar-benar berlebihan. “Trus,
kok ikut acara ini?”
“Aku salah satu personil band sekolah. Pengisi acara juga.”
Dia mengagguk-angguk. “Tapi, mau dong mencoba main teater sama Kak
Fathan?”
Kak Fathan itu siapa lagi?
“Ha?” Serius, aku benar-benar nggak tahu maksudnya. “Main teater?”
Cowok itu mengangguk sambil tersenyum.
“Aku nggak bisa teater. Nyanyi aja, deh!” tawarku.
“Baca puisi aja.”
Suara cowok di belakangku membuatku melihat ke arahnya. Ah, ternyata dia si cowok plontos yang bikin Gisel terpesona.
Dari pada suruh berakting, sepertinya baca puisi lebih mending. “Oke.”
Kutarik selembar kertas dari saku belakang celana jeans-ku. Aku ingat menulis sebuah puisi
yang tadi malam kubaca di majalah langganan kakakku. Dan tadi, aku iseng
memasukkan ke dalam saku untuk kutunjukkan pada Stevan. Mungkin, puisi itu bisa
memancing kreativitasnya untuk menciptakan lagu baru untuk band kami.
“Kalah… Kalau, karya Tan,” kubaca judul dan nama penulisnya. Aku
terdiam sesaat, melirik dari balik bulu mata kesepenjuru batas penglihatanku.
Mereka tampak memperhatikanku.
Ah, kenapa aku berdebar? Aku, kan sudah biasa menghadapi situasi
seperti ini? Tapi, biasanya aku bernyanyi, sih. Sekarang, aku harus baca puisi.
Ternyata, rasanya tetap berbeda.
“Maaf, mas. Sebentar!” aku berbisik pada cowok yang masih berdiri
di sampingku.
Aku langsung turun dari panggung. Menghampiri teman-temanku. “Stev,
pinjam gitarmu!” Ada sebuah ide muncul di dalam tempurung kepalaku.
Stev dengan bingung menyerahkan gitar akustik kesayangannya.
Dengan cepat, aku kembali ke atas panggung. Aku tak langsung
duduk, tapi mengambil dudukan mic agar aku bisa memainkan gitarku dengan
leluasa. Dan, meminta cowok yang memanggilku tadi untuk memegangi selembar
kertas yang tampak lusuh agar bisa kubaca.
“Kalah….Kalau, karya Tan.” Kuulang membaca judulnya dengan
intonasi lebih jelas.
Kemudian, kupetik gitar Stev dengan melodi yang lahir begitu saja.
Pias gemulai redup menawanku
Menciptakan siluet bayang-bayang pemenuh kalbu
Kelu…
Kenapa aku teramat kelu dan malu?
Ah… itukah caraku memilikimu?
Denting
gitar semakin lancar kupetik.
Bianglala menerjang sinar rembulan
Menyampaikan pesan diam-diam dari hati
kasmaran
Dara… Masihkah kau tersenyum dengan lekuk pipimu?
Menambat hatiku dengan kelebat hijabmu
Merayuku dengan syahdu suaramu
Dara…tahukah engkau, aku mencintaimu?
Tak perlu kata…
Karena aku terlalu bisu setiap kau mencumbui
mataku.
Maaf…
Aku tak mampu bertutur merdu tentang cinta…
Kuulang lagi bait pertamanya, namun sekarang kumusikalisasikan
dengan pelan, dan sedikit melankolis. Ternyata, saat kuselesaikan penampilanku,
tepuk tangan menyambutku.
Aku tersenyum, “Terima kasih.”
Aku langsung turun dari panggung, tak peduli pada orang-orang di
belakangku tadi.
Apa kalian puas mengerjaiku? Makanya,
jangan main-main sama aku!
***
FATHAN
Jantungku berhenti beberapa second
saat gadis agak boyish yang tadi
di panggil Gavin─menyebut judul puisi yang dibacanya.
“Kalah…Kalau, karya Tan.” Ucapnya mantap.
Itu puisiku yang kukirim ke redaksi majalah beberapa hari yang
lalu. Majalah itu memang selalu menampilkan puisiku di kolomnya. Tapi, aku tak
menyangka puisi itu akan di baca di sini, di depan Retno.
Pias gemulai redup menawanku
Menciptakan siluet bayang-bayang pemenuh kalbu
Kelu…
Kenapa aku teramat kelu dan malu?
Ah… itukah caraku memilikimu?
Petikan gitarnya dan puisiku beriringan syahdu. Dia ternyata
sangat piawai melakukan tugasnya.
Bianglala menerjang sinar rembulan
Menyampaikan pesan diam-diam dari hati
kasmaran
Dara… Masihkah kau tersenyum dengan lekuk pipimu?
Menambat hatiku dengan kelebat hijabmu
Merayuku dengan syahdu suaramu
Kulirik Retno yang berada di sisi Sinta. Dia tampak menyimak.
Pandangannya lurus pada gadis bernama Tiara, kalau aku tak salah dengar.
Perlahan, saat Tiara mengubah puisi itu menjadi lagu, kulihat
Retno mengigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Dan, setelah sesi ini selesai,
dialah yang paling semangat bertepuk tangan.
Retno, kamu tahu, Puisi itu kamu? Ya,
kamu… kamu yang membuatku kelu.
Rasanya, aku ingin berterima kasih pada gadis itu. Karena dia,
pesanku tersampaikan pada Retno. Meskipun aku sadar, wanita itu tak akan menangkap
maksudku, bahkan tak akan menyadari siapa penulis puisinya.
Tak apa, setidaknya dia menyukai puisiku untuknya.
***




![[Wattpad] Novel - After a go](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJP8_ylNnn8AsiTbsS1ow5vyY10gpEyt_SzREkYHoj3wFxFAIMOI2GDpv-ShfLqXrsvapn0BeM2JwEstx1nnI2lVfY5t1yBkMeXfQ7yQ8BMG06C8SH9ji-VxtZaSdCsZWhCpzsm5iS1g4/s1600/after+a+go.jpg)
![[Wattpad] Novel - And, It's You](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPg6OskjvXbGRqmntuQHKVDI2anbqXOlqFjxUv3cVETYXBH1f13Tuki5rICEx-u2lasA03AbY7S_phMfg_8bem8oSlP5A15waMfQzRtPTbuXlxfekyKEcqaMNeNrU7HP0R3182WgIFpVc/s1600-r/and+its+you.jpg)

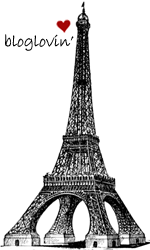






























wah keren banget ini. semua tokoh berhubungan dalam satu cerita. tapi masih banyak misteri yang masih belum terungkap. seperti siapa Andi?
ReplyDeleteIya, memang masih banyak rahasia-nya :D
ReplyDeleteTerima kasih sudah membaca dan mampir :')